Ekonomi Mengayuh Sepeda
Di hari kejepit nasional. Jalanan tidak seramai hari biasa. Ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, terbilang sepi. Tepat pukul 22.30 telepon selular saya bergetar. Seorang kawan, Muhardi Munaf, sosok pengusaha dari Sumatera Barat, yang sudah hijrah berbisnis ke Jakarta sejak penghujung 1990-an, menyapa dari seberang telepon.
Haji Ad - - begitu Muhardi akrab disapa - - mengajak ngobrol di malam Sabtu itu. Kami memilih tempat terbuka di Café Olala, di Jakarta Teater, di seberang Sarinah, Jl.Thamrin, Jakarta Pusat. Café itu buka 24 jam, ada bagian beranda ber-AC alam. Untuk membuat suasana lebih teduh, dua kipas besar yang mengeluarkan kabut air mengerakkan angin dingin.
Ketika 1986, saya masih bekerja di majalah SWA. Muhardi - - akrab disapa Haji Ad - - adalah salah satu sumber berita saya. Kala itu kami membuat laporan utama tentang kampiun bisnis di berbagai daerah. Adalah Haji Ad, mewakili sosok pengusaha properti di Padang. Prestasinya menyulap bangunan Pasaraya, Padang. Bagian atas pasar ia bangun layaknya mall. Maka berdirilah Duta Plaza, mall pertama di Padang kala itu. Penyewa utamamya Matahari Department Store.
Ketika usai mewawancarainya di kantornya di Padang, seorang staf Humas, Boy Lestari, mengajak saya makan, mentraktir, menitipkan amplop berisi segepok uang dari Haji Ad.
Sejak awal menjadi jurnalis, saya sudah mengharamkan diri menerima yang begitu. Bahkan tawaran mengantarkan ke airport pun ketika kembali ke Jakarta saya tolak. Sikap itulah kemudian membawa saya menjadi berteman dengan Haji Ad.
Di luar dugaan saya manager Humas Haji Ad dulu, Boy Lestari, sejak dua tahun lalu saya ketahui sudah menjadi salah satu ulama besar di Padang kini. Jamaahnya ribuan.
Penampilan Boy bersorban putih bagaikan beratribut Tuanku Imam Bonjol. Ia sudah macam Aa Gym di kala top. Tidak terbayangkan oleh saya seorang Boy Lestari yang kini dai itu. Konon dia berdakwah sudah lintas kota di Sumatera.
Waktu memang cepat berlalu. Berganti.
Setelah memarkir mobil sport merah produksi Mitshubishi, Haji Ad langsung duduk di depan saya yang terlebih dulu datang. Malam itu ia berbaju batik lengen pendek bercelana pendek. Suasana memang santai.
“Bagaimana hidup?” ujar Haji Ad menjabat erat.
Saya menjawab: Badan sangat sehat. Kantung tipis
Saya bertanya, bagaimana dengan bisnis properti di DKI, yang tampaknya kian heboh. Di sebuah milis, Forum Pembaca Kompas saya baca bahwa ada ajakan demo untuk melarang pembangunan 13 mall baru di Jakarta.
Di Jakarta, Haji Ad memang bukan sosok pemain properti besar. Tetapi bisnisnya masih konsisten di situ. Lima tahun lalu misalnya ia menyulap bagian lantai atas Pasar Cipete, Jakarta Selatan - - tempat penjualan onderdil mobil - - yang di bawahnya terkesan kumuh. Lantai atas setelah dibangun dikembangkan berbagai kursus dan pendidikan kejuruan. Suasana sudah semacam ruangan hotel bintang tiga.
Suatu hari ia bercerita, pernah salah satu pemilik kelompok usaha properti, punya beberapa Mall bertajuk Town Square, antara lain di bilangan Serpong, Banten, menawarkan mengisi luas lantai mallnya yang masih kosong. Luasnya mencapai 40.000 meter persegi (empat hektar). Hingga kini baru sekitar 30 % saja terisi. Beberapa bagian, penyewa justeru pengembang sendiri yang mengisi, antara lain memenuhi dengan arena play ground.
Kendati suplai mall, apartment, ruang perkantoran, kini bisa dibilang berlebih, pembangunan seakan enggan berhenti. Sudah lama hal ini menjadi tanya di dalam diri saya. Bagaimana pengembang mencari pasar? Siapa yang mengisi?
HASIL riset perusahaan konsultan properti global Jones Lang LaSalle, yang dipublikasikan pada penghujung 2007 lalu menyebutkan ada tiga mal mewah segera beroperasi. Yakni mal terpadu yang terintegrasi dengan hunian kondominium Grand Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Pacific Place di kompleks Sudirman Central Business District (SCBD), serta pembangunan Mal Kelapa Gading Tahap 5 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
"Ada tambahan 196.000 meter persegi ruang ritel mewah di Jakarta. Sebanyak 260.000 meter persegi lainnya dipastikan akan masuk ke pasar mulai tahun depan," kata Lucy Rumantir, Chairman Jones Lang LaSalle (Indonesia), seperti dikutip Kompas Cyber, November 2007 lalu.
Penyewa ruang ritel mewah di Jakarta, umumnya didominasi industri makanan dan entertainment. Lucy menyebutkan, rata-rata tarif sewa per meter persegi upper class retail ini mencapai 492 dolar AS per meter persegi per tahun atau hampir Rp 4,5 juta dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dolar AS. Dibandingkan tahun lalu, tren tarif sewa mal mewah di Jakarta naik tipis sekitar 1,3 persen. Capital values mal mewah di Jakarta ini mencapai 3.249 dolar AS per meter persegi.
Tarif sewa mal mewah di Jakarta masih terbilang paling murah dibanding tarif sewa mal mewah di sejumlah kota di Asia. Di Hong Kong yang dikenal sebagai surga belanja di Asia, tarif sewa toko saja yang berlokasi di jalan-jalan utama kota mencapai 4.642 dolar AS.
Sementara, tarif sewa ruang di mal-mal di jalan-jalan utama Hong Kong mencapai 4.956 dolar AS. Di Shanghai, tarif sewa mal mewah mencapai 1.876 dolar AS, di Singapura 2.944 dolar AS dan di Kuala Lumpur (pusat kota) mencapai 762 dolar AS per meter persegi per tahun.
Membaiknya daya beli konsumen kaya di Jakarta, dan sekitarnya membuat permintaan akan ruang sewa mal mewah di Jakarta meningkat sepanjang kuartal II 2007 lalu.
"Tapi pasar masih akan terus dibayangi oleh membanjirnya pasokan ruang sewa baru di tahun depan. Kondisi ini akan memicu persaingan yang sangat ketat di pasar antar pengelola mal, " ujar Lucy
Jika penyewa untuk produk kalangan atas, sebagaimana bisa dilihat di mall Grand Indonesia dan SCBD, kini memang terisi. Tetapi sebaliknya mall di kelas menengah, macam di Serpong Town Square, Serpong, tak sampai 50% terpenuhi.
Jika Anda berjalan-jalan ke Mangga Dua Square, hari ini, suasana ruang kosong melompong dapat ditemui di lantai dua ke atas. Bagian bawah juga banyak ruang yang tak berpenghuni.
Saya bertanya kepada Haji Ad, sesungguhnya apa yang terjadi, booming kah bisnis properti?
Dia tertawa, menatap saya sambil mengisap dalam rokoknya.
“Yang terjadi sesungguhnya ekonomi mengyauh sepeda,” ujar Haji Ad.
Apa pula ekonomi mengayuh sepeda itu?
Dari sepuluh penegmbang besar di Jakarta yang diamatinya, semuanya memang memulai usaha dengan memiliki equity kecil untuk membangun proyek mega. Ketika seseorang membangun, katakana mall X, ia sertakan equitynya tak sampai 35% dari total investasi. Sisanya dana bank.
Proyek berjalan. Mereka memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR) - - bila belum punya, mereka membeli BPR - - atau Bank Umum skala kecil. Kredit besar mereka dapat dari Bank besar pemerintah. Bunga setelah proyek berjalan dilunasi via BPR pengembang.
“Proyek selesai, bunga dan ciciltan hutang harus dibayar, dan ternyata ruang mall X kosong, “ kisah Haji Ad pula, “Maka mereka mengakali lagi dengan wajib membangun proyek kedua. Proyek kedua menciptakan proyek pertama seakan emnjadi sehat. Karena bunga dan cicilan bisa dilancarkan dari cara mengakali proyek kedua.”
“Bermain” di proyek kedua. Beban bunga, biaya dan cicilan hutang di proyek pertama, dipikul dari memarkup pembangunan mall Y, proyek kedua.
Misal nilai invetasi Rp 400 miliar, disulap menjadi Rp 600 miliar. “Enam ratus, biasanya untuk komisi direksi bank lima persen, sisa mark up yang Rp 170 miliar menutupi kebutuhan biaya di proyek pertama.”
Begitu seterusnya. Untuk menutupi proyek kedua dan menambah subsidi proyek pertama, pengembang membangun lagi mall ketiga, sebut saja mall Z. Di mall Z laku mark up juga terjadi. Lalu mulai “aman” lagi proyek kedua, dan proyek ketiga pun dapat dibangun.
Di tengah situasi cash flow mulai ketat, pengembang tidak kehilangan akal. Ia mencari pihak tertentu yang punya lahan. Karena punya porto folio, maka kerjasama operasi (KSO) dengan pemilik lahan dapat dilakukan. Dan tanah baru yang didapat dijaminkan lagi ke bank. Dapat lagi darah baru untuk membangun mall baru. Seluruh usaha seakan berjalan, wujud bangunan tampak mencakar langit.
Logika itu KSO masuk akal. Kendati Anda pun punya lahan luas di Jakarta, jika tak punya porto folio pengembang besar, tidak kredibel di mata bank, macam mana pula kredit bank bisa cair.
Di tahun yang berjalan, mall pertama karena sudah ada yang lima tahun umurnya, oleh pemilik dilakukann taksasi ulang nilai asset. “Tentu sudah mengalami kenaikan nilai, baik tanah, bangunan,” ujar Haji Ad.
Karena memiliki kenaikan nilai aset, maka pengembang bisa “menjual” lagi mall pertama tadi untuk mendapatkan kredit di bank lain - - bukan bank pemberi kredit awal - - atau dengan istilah take over kredit.
Karena usaha berputar, bangunan terus berjalan, loan-loan baru terus bertambah, maka akal-akalan melakukan go public, IPO di pasar modal pun disulap. Dapatlah pengembang dana murah di masyarakat, untuk sedikit memperbaiki struktur pemodalan. Bisa jadi hanya dengan menjual 15% saja saham holding perusahaan pengembang (unit properti) ke pasar modal.
Di lain sisi pasar properti tetap belum bergairah, maka pembiayaan harus terus dilakukan pengembang, maka loan baru dari proyek baru harus terus didapat. Begitu seterusnya, demi survival.
“Maka,” kata Haji Ad, “Seorang kawan pengembang ketika menandatangi akad kredit Rp 600 miliar, ia merasa datar dan tak happy.”
Pasalnya?
Hal itu sudah seakan kewajiban yang mutlak dilalui. Bila tidak dilakukan, ya macam mengayuh sepeda, bila berhenti mengayuh, maka seluruh bisnis kelompok pengembang itu ambrol struktur pembiayaannya, struktur permodalannya. Kolaps.
Haji Ad yakin seyakin-yakinnya laku itu dijalani pula oleh pengembang apartment , perkantoran. Sehingga hari ini kita melihatlah pembangunan properti itu “bergerak”. Ia juga yakin bahwa 50% kredit perbankan mengalir ke 10 besar pengembang, termasuk nama besar macam Ciputra, Grup Lippo, Grup Bakrie, Agung Sedayu, Podomoro, Gapura Prima dan seterus itu.
Mereka semua berjalan ibarat mengayuh sepeda, yang harus terus dipacu - - yang sesungguhnya sudah tidak prudent itu.
Celakannya bank pemberi kredit juga menjadi terperangkap ke dalam ekonomi mengayuh sepeda itu. Bila kredit dihentikan, maka kredit macet tambun di properti akan terjadi, bank kembali kolaps.
Saya geleng-geleng kepala mendengar paparan haji Ad. Itu artinya siklus lima tahunan, sepuluh tahunan di dunia properti memang selalu terulang dan berulang.
Sehingga bila kalangan usaha menengah dan kecil kini berteriak ke ujung langit, mengharapkan perbankan menggerakkan sektror riil, hingga suara parau bahkan habis, bank tak akan menggubris.
Mereka bermain gampang di properti besar, mereka cuma bermain di kredit consumer, KPR, kendaraan dan kartu kredit.
Mereka lupa bahwa yang meraka bangun hanya sebuah fatamorgana ekonomi mengayuh sepeda itu.
SETELAH setahun pemerintahannya banyak pihak mengingatkan SBY-Kalla, agar menggerakkan sektor ril, jangan cuma terpaku ke ekonomi makro. Sayang kini semuanya seakan sudah terlambat. Pekan lalu kita baru mendengar bahwa SBY mengakui keadaan sulit, apalagi kenaikan harga BBM di pasaran global terus terjadi. Sebuah nada laksana melempar handuk putih diring tinju.
Logika terbalik-balik justeru telah pula diuarkan SBY kini, yakni menghimbau untuk melakukan penghematan. Di negara yang maju, acuan pemakaian elektrikal, menjadi kunci kemajuan ekonomi.
Rakyat di negeri lebih beradab dihimbau membelanjakan uang, agar eknomi berputar. Sebaliknya hari ini penghematan harus kita lakukan di sini, di tengah keadaan ekonomi macam mengayuh sepeda dipaksakan berhenti di semua lini.
Bila sudah begini, Anda bisa menjawab sendiri. SBY minta berhenti “mengayuh” sepeda. Bila berhenti di jalan datar, sang sepeda tidak lagi Anda kayuh?
Lebih celaka, diberbagai lini masayarakat kini seakan berlomba-lomba masuk ke kancah politik. Bisa jadi rakyat kebanyakan terbius melihat ada anggota DPR dari semula berjalan kaki dan mengontrak rumah di gang becek, kini sudah naik Bentley Arnage, berumah di Kebayoran Baru, Jakarta.
Jas mereka sudah pula Gucci, sudah pula Salvatore Ferragamo.
Sebaliknya kini, tidak ada gerakan nasional mengembangkan berbagai produk baru, mengembangkan jasa berbagai jasa baru yang masuk ke pasaran.
Asset BUMN strategis yang ada, malah kini harus dijual lagi untuk menutupi APBN.
Bila sudah begini, seribu Phd, seribu yang mengaku brilian pun di pemerintahan, menjadi "tertawaan" tukang becak, "tertawaan" pemulung yang lewat di depan rumah saya, memang: di saat sulit bisanya jual asset negara, semua orang bisa begitu, termasuk anak-anak yang tak tamat sekolah lanjutan.
Waktu di arloji saya di Jumat malam itu sudah pukul 02,30. Sambil menumpang di mobil sport Haji Ad yang mewah, saya menikmati pula bayangan menjadi pengembang properti, yang sesungguhnya hanya menumpang kaya dari perputaran proyek.
Saya teringat akan keterangan seorang kawan yang meminta sponsor untuk sebuah event diskusi belum lama ini ke seorang pengembang. Untuk angka Rp 10 juta saja sang pengembang itu keberatan.
Malam tadi saya menjadi tahu dan sadar betul jawabannya: mereka semua sesungguhnya “kere”, kendati investasinya di properti setidaknya Rp 5 triliun setahun.
From :
http://www.apakabar.ws/content/view/1756/88888889/
Haji Ad - - begitu Muhardi akrab disapa - - mengajak ngobrol di malam Sabtu itu. Kami memilih tempat terbuka di Café Olala, di Jakarta Teater, di seberang Sarinah, Jl.Thamrin, Jakarta Pusat. Café itu buka 24 jam, ada bagian beranda ber-AC alam. Untuk membuat suasana lebih teduh, dua kipas besar yang mengeluarkan kabut air mengerakkan angin dingin.
Ketika 1986, saya masih bekerja di majalah SWA. Muhardi - - akrab disapa Haji Ad - - adalah salah satu sumber berita saya. Kala itu kami membuat laporan utama tentang kampiun bisnis di berbagai daerah. Adalah Haji Ad, mewakili sosok pengusaha properti di Padang. Prestasinya menyulap bangunan Pasaraya, Padang. Bagian atas pasar ia bangun layaknya mall. Maka berdirilah Duta Plaza, mall pertama di Padang kala itu. Penyewa utamamya Matahari Department Store.
Ketika usai mewawancarainya di kantornya di Padang, seorang staf Humas, Boy Lestari, mengajak saya makan, mentraktir, menitipkan amplop berisi segepok uang dari Haji Ad.
Sejak awal menjadi jurnalis, saya sudah mengharamkan diri menerima yang begitu. Bahkan tawaran mengantarkan ke airport pun ketika kembali ke Jakarta saya tolak. Sikap itulah kemudian membawa saya menjadi berteman dengan Haji Ad.
Di luar dugaan saya manager Humas Haji Ad dulu, Boy Lestari, sejak dua tahun lalu saya ketahui sudah menjadi salah satu ulama besar di Padang kini. Jamaahnya ribuan.
Penampilan Boy bersorban putih bagaikan beratribut Tuanku Imam Bonjol. Ia sudah macam Aa Gym di kala top. Tidak terbayangkan oleh saya seorang Boy Lestari yang kini dai itu. Konon dia berdakwah sudah lintas kota di Sumatera.
Waktu memang cepat berlalu. Berganti.
Setelah memarkir mobil sport merah produksi Mitshubishi, Haji Ad langsung duduk di depan saya yang terlebih dulu datang. Malam itu ia berbaju batik lengen pendek bercelana pendek. Suasana memang santai.
“Bagaimana hidup?” ujar Haji Ad menjabat erat.
Saya menjawab: Badan sangat sehat. Kantung tipis
Saya bertanya, bagaimana dengan bisnis properti di DKI, yang tampaknya kian heboh. Di sebuah milis, Forum Pembaca Kompas saya baca bahwa ada ajakan demo untuk melarang pembangunan 13 mall baru di Jakarta.
Di Jakarta, Haji Ad memang bukan sosok pemain properti besar. Tetapi bisnisnya masih konsisten di situ. Lima tahun lalu misalnya ia menyulap bagian lantai atas Pasar Cipete, Jakarta Selatan - - tempat penjualan onderdil mobil - - yang di bawahnya terkesan kumuh. Lantai atas setelah dibangun dikembangkan berbagai kursus dan pendidikan kejuruan. Suasana sudah semacam ruangan hotel bintang tiga.
Suatu hari ia bercerita, pernah salah satu pemilik kelompok usaha properti, punya beberapa Mall bertajuk Town Square, antara lain di bilangan Serpong, Banten, menawarkan mengisi luas lantai mallnya yang masih kosong. Luasnya mencapai 40.000 meter persegi (empat hektar). Hingga kini baru sekitar 30 % saja terisi. Beberapa bagian, penyewa justeru pengembang sendiri yang mengisi, antara lain memenuhi dengan arena play ground.
Kendati suplai mall, apartment, ruang perkantoran, kini bisa dibilang berlebih, pembangunan seakan enggan berhenti. Sudah lama hal ini menjadi tanya di dalam diri saya. Bagaimana pengembang mencari pasar? Siapa yang mengisi?
HASIL riset perusahaan konsultan properti global Jones Lang LaSalle, yang dipublikasikan pada penghujung 2007 lalu menyebutkan ada tiga mal mewah segera beroperasi. Yakni mal terpadu yang terintegrasi dengan hunian kondominium Grand Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Pacific Place di kompleks Sudirman Central Business District (SCBD), serta pembangunan Mal Kelapa Gading Tahap 5 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
"Ada tambahan 196.000 meter persegi ruang ritel mewah di Jakarta. Sebanyak 260.000 meter persegi lainnya dipastikan akan masuk ke pasar mulai tahun depan," kata Lucy Rumantir, Chairman Jones Lang LaSalle (Indonesia), seperti dikutip Kompas Cyber, November 2007 lalu.
Penyewa ruang ritel mewah di Jakarta, umumnya didominasi industri makanan dan entertainment. Lucy menyebutkan, rata-rata tarif sewa per meter persegi upper class retail ini mencapai 492 dolar AS per meter persegi per tahun atau hampir Rp 4,5 juta dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dolar AS. Dibandingkan tahun lalu, tren tarif sewa mal mewah di Jakarta naik tipis sekitar 1,3 persen. Capital values mal mewah di Jakarta ini mencapai 3.249 dolar AS per meter persegi.
Tarif sewa mal mewah di Jakarta masih terbilang paling murah dibanding tarif sewa mal mewah di sejumlah kota di Asia. Di Hong Kong yang dikenal sebagai surga belanja di Asia, tarif sewa toko saja yang berlokasi di jalan-jalan utama kota mencapai 4.642 dolar AS.
Sementara, tarif sewa ruang di mal-mal di jalan-jalan utama Hong Kong mencapai 4.956 dolar AS. Di Shanghai, tarif sewa mal mewah mencapai 1.876 dolar AS, di Singapura 2.944 dolar AS dan di Kuala Lumpur (pusat kota) mencapai 762 dolar AS per meter persegi per tahun.
Membaiknya daya beli konsumen kaya di Jakarta, dan sekitarnya membuat permintaan akan ruang sewa mal mewah di Jakarta meningkat sepanjang kuartal II 2007 lalu.
"Tapi pasar masih akan terus dibayangi oleh membanjirnya pasokan ruang sewa baru di tahun depan. Kondisi ini akan memicu persaingan yang sangat ketat di pasar antar pengelola mal, " ujar Lucy
Jika penyewa untuk produk kalangan atas, sebagaimana bisa dilihat di mall Grand Indonesia dan SCBD, kini memang terisi. Tetapi sebaliknya mall di kelas menengah, macam di Serpong Town Square, Serpong, tak sampai 50% terpenuhi.
Jika Anda berjalan-jalan ke Mangga Dua Square, hari ini, suasana ruang kosong melompong dapat ditemui di lantai dua ke atas. Bagian bawah juga banyak ruang yang tak berpenghuni.
Saya bertanya kepada Haji Ad, sesungguhnya apa yang terjadi, booming kah bisnis properti?
Dia tertawa, menatap saya sambil mengisap dalam rokoknya.
“Yang terjadi sesungguhnya ekonomi mengyauh sepeda,” ujar Haji Ad.
Apa pula ekonomi mengayuh sepeda itu?
Dari sepuluh penegmbang besar di Jakarta yang diamatinya, semuanya memang memulai usaha dengan memiliki equity kecil untuk membangun proyek mega. Ketika seseorang membangun, katakana mall X, ia sertakan equitynya tak sampai 35% dari total investasi. Sisanya dana bank.
Proyek berjalan. Mereka memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR) - - bila belum punya, mereka membeli BPR - - atau Bank Umum skala kecil. Kredit besar mereka dapat dari Bank besar pemerintah. Bunga setelah proyek berjalan dilunasi via BPR pengembang.
“Proyek selesai, bunga dan ciciltan hutang harus dibayar, dan ternyata ruang mall X kosong, “ kisah Haji Ad pula, “Maka mereka mengakali lagi dengan wajib membangun proyek kedua. Proyek kedua menciptakan proyek pertama seakan emnjadi sehat. Karena bunga dan cicilan bisa dilancarkan dari cara mengakali proyek kedua.”
“Bermain” di proyek kedua. Beban bunga, biaya dan cicilan hutang di proyek pertama, dipikul dari memarkup pembangunan mall Y, proyek kedua.
Misal nilai invetasi Rp 400 miliar, disulap menjadi Rp 600 miliar. “Enam ratus, biasanya untuk komisi direksi bank lima persen, sisa mark up yang Rp 170 miliar menutupi kebutuhan biaya di proyek pertama.”
Begitu seterusnya. Untuk menutupi proyek kedua dan menambah subsidi proyek pertama, pengembang membangun lagi mall ketiga, sebut saja mall Z. Di mall Z laku mark up juga terjadi. Lalu mulai “aman” lagi proyek kedua, dan proyek ketiga pun dapat dibangun.
Di tengah situasi cash flow mulai ketat, pengembang tidak kehilangan akal. Ia mencari pihak tertentu yang punya lahan. Karena punya porto folio, maka kerjasama operasi (KSO) dengan pemilik lahan dapat dilakukan. Dan tanah baru yang didapat dijaminkan lagi ke bank. Dapat lagi darah baru untuk membangun mall baru. Seluruh usaha seakan berjalan, wujud bangunan tampak mencakar langit.
Logika itu KSO masuk akal. Kendati Anda pun punya lahan luas di Jakarta, jika tak punya porto folio pengembang besar, tidak kredibel di mata bank, macam mana pula kredit bank bisa cair.
Di tahun yang berjalan, mall pertama karena sudah ada yang lima tahun umurnya, oleh pemilik dilakukann taksasi ulang nilai asset. “Tentu sudah mengalami kenaikan nilai, baik tanah, bangunan,” ujar Haji Ad.
Karena memiliki kenaikan nilai aset, maka pengembang bisa “menjual” lagi mall pertama tadi untuk mendapatkan kredit di bank lain - - bukan bank pemberi kredit awal - - atau dengan istilah take over kredit.
Karena usaha berputar, bangunan terus berjalan, loan-loan baru terus bertambah, maka akal-akalan melakukan go public, IPO di pasar modal pun disulap. Dapatlah pengembang dana murah di masyarakat, untuk sedikit memperbaiki struktur pemodalan. Bisa jadi hanya dengan menjual 15% saja saham holding perusahaan pengembang (unit properti) ke pasar modal.
Di lain sisi pasar properti tetap belum bergairah, maka pembiayaan harus terus dilakukan pengembang, maka loan baru dari proyek baru harus terus didapat. Begitu seterusnya, demi survival.
“Maka,” kata Haji Ad, “Seorang kawan pengembang ketika menandatangi akad kredit Rp 600 miliar, ia merasa datar dan tak happy.”
Pasalnya?
Hal itu sudah seakan kewajiban yang mutlak dilalui. Bila tidak dilakukan, ya macam mengayuh sepeda, bila berhenti mengayuh, maka seluruh bisnis kelompok pengembang itu ambrol struktur pembiayaannya, struktur permodalannya. Kolaps.
Haji Ad yakin seyakin-yakinnya laku itu dijalani pula oleh pengembang apartment , perkantoran. Sehingga hari ini kita melihatlah pembangunan properti itu “bergerak”. Ia juga yakin bahwa 50% kredit perbankan mengalir ke 10 besar pengembang, termasuk nama besar macam Ciputra, Grup Lippo, Grup Bakrie, Agung Sedayu, Podomoro, Gapura Prima dan seterus itu.
Mereka semua berjalan ibarat mengayuh sepeda, yang harus terus dipacu - - yang sesungguhnya sudah tidak prudent itu.
Celakannya bank pemberi kredit juga menjadi terperangkap ke dalam ekonomi mengayuh sepeda itu. Bila kredit dihentikan, maka kredit macet tambun di properti akan terjadi, bank kembali kolaps.
Saya geleng-geleng kepala mendengar paparan haji Ad. Itu artinya siklus lima tahunan, sepuluh tahunan di dunia properti memang selalu terulang dan berulang.
Sehingga bila kalangan usaha menengah dan kecil kini berteriak ke ujung langit, mengharapkan perbankan menggerakkan sektror riil, hingga suara parau bahkan habis, bank tak akan menggubris.
Mereka bermain gampang di properti besar, mereka cuma bermain di kredit consumer, KPR, kendaraan dan kartu kredit.
Mereka lupa bahwa yang meraka bangun hanya sebuah fatamorgana ekonomi mengayuh sepeda itu.
SETELAH setahun pemerintahannya banyak pihak mengingatkan SBY-Kalla, agar menggerakkan sektor ril, jangan cuma terpaku ke ekonomi makro. Sayang kini semuanya seakan sudah terlambat. Pekan lalu kita baru mendengar bahwa SBY mengakui keadaan sulit, apalagi kenaikan harga BBM di pasaran global terus terjadi. Sebuah nada laksana melempar handuk putih diring tinju.
Logika terbalik-balik justeru telah pula diuarkan SBY kini, yakni menghimbau untuk melakukan penghematan. Di negara yang maju, acuan pemakaian elektrikal, menjadi kunci kemajuan ekonomi.
Rakyat di negeri lebih beradab dihimbau membelanjakan uang, agar eknomi berputar. Sebaliknya hari ini penghematan harus kita lakukan di sini, di tengah keadaan ekonomi macam mengayuh sepeda dipaksakan berhenti di semua lini.
Bila sudah begini, Anda bisa menjawab sendiri. SBY minta berhenti “mengayuh” sepeda. Bila berhenti di jalan datar, sang sepeda tidak lagi Anda kayuh?
Lebih celaka, diberbagai lini masayarakat kini seakan berlomba-lomba masuk ke kancah politik. Bisa jadi rakyat kebanyakan terbius melihat ada anggota DPR dari semula berjalan kaki dan mengontrak rumah di gang becek, kini sudah naik Bentley Arnage, berumah di Kebayoran Baru, Jakarta.
Jas mereka sudah pula Gucci, sudah pula Salvatore Ferragamo.
Sebaliknya kini, tidak ada gerakan nasional mengembangkan berbagai produk baru, mengembangkan jasa berbagai jasa baru yang masuk ke pasaran.
Asset BUMN strategis yang ada, malah kini harus dijual lagi untuk menutupi APBN.
Bila sudah begini, seribu Phd, seribu yang mengaku brilian pun di pemerintahan, menjadi "tertawaan" tukang becak, "tertawaan" pemulung yang lewat di depan rumah saya, memang: di saat sulit bisanya jual asset negara, semua orang bisa begitu, termasuk anak-anak yang tak tamat sekolah lanjutan.
Waktu di arloji saya di Jumat malam itu sudah pukul 02,30. Sambil menumpang di mobil sport Haji Ad yang mewah, saya menikmati pula bayangan menjadi pengembang properti, yang sesungguhnya hanya menumpang kaya dari perputaran proyek.
Saya teringat akan keterangan seorang kawan yang meminta sponsor untuk sebuah event diskusi belum lama ini ke seorang pengembang. Untuk angka Rp 10 juta saja sang pengembang itu keberatan.
Malam tadi saya menjadi tahu dan sadar betul jawabannya: mereka semua sesungguhnya “kere”, kendati investasinya di properti setidaknya Rp 5 triliun setahun.
From :
http://www.apakabar.ws/content/view/1756/88888889/
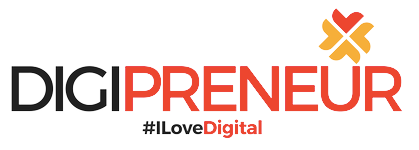

Post a Comment